Ketika politisi bicara soal larangan VPN dengan dalih “melindungi anak” atau “mencegah konten terlarang”, ada satu hal besar yang terancam: kebebasan sipil di dunia digital.
VPN = Alat Bertahan Hidup di Negara Otoriter
Bagi banyak orang di negara dengan rezim otoriter, VPN bukan sekadar aplikasi, tapi lifeline. Lewat VPN, mereka bisa mengakses berita independen, berkomunikasi tanpa disensor, bahkan melindungi identitas dari pengawasan negara. Kalau akses VPN diputus, suara-suara kritis bisa dibungkam dengan mudah.
Efek Psikologis: Self-Censorship
Tanpa VPN, orang bakal lebih hati-hati bersuara di internet. Ketakutan diawasi mendorong self-censorship—orang memilih diam daripada berisiko dihukum. Ini menciptakan masyarakat yang pasif dan makin jauh dari nilai kebebasan berpendapat.
Marginalized Communities yang Paling Rugi
Komunitas yang terpinggirkan — dari aktivis HAM, jurnalis independen, hingga kelompok minoritas — adalah pihak pertama yang bakal kehilangan perlindungan. Mereka yang selama ini mengandalkan VPN buat bersuara aman akan terekspos ke doxing, persekusi, bahkan kriminalisasi.
Privasi Jadi Mitos
Larangan VPN otomatis berarti privasi online makin mustahil. ISP (Internet Service Provider) atau bahkan pemerintah bisa melacak aktivitas digital dengan lebih mudah. Bagi generasi muda yang tumbuh di era internet, ini bisa terasa kayak kembali ke zaman di mana setiap langkah kita diawasi.
Kontra Produktif Buat Demokrasi
Ironisnya, banyak politisi yang mendorong larangan VPN di negara demokrasi dengan alasan moral. Padahal, demokrasi sejati justru bertumpu pada akses bebas terhadap informasi dan kebebasan berpendapat. Larangan VPN malah bikin negara demokrasi makin mirip rezim yang suka menyensor.
Kesimpulan
Melarang VPN bukan sekadar keputusan teknis soal internet, tapi keputusan politik yang bisa memangkas hak-hak dasar manusia. Dari kebebasan berpendapat, hak atas privasi, sampai hak untuk mengakses informasi, semuanya bisa runtuh hanya gara-gara regulasi yang terlalu berlebihan.
Kalau kebebasan digital ini hilang, pertanyaannya tinggal satu: apakah kita masih benar-benar hidup di era demokrasi digital, atau malah masuk ke bab baru pengawasan massal?

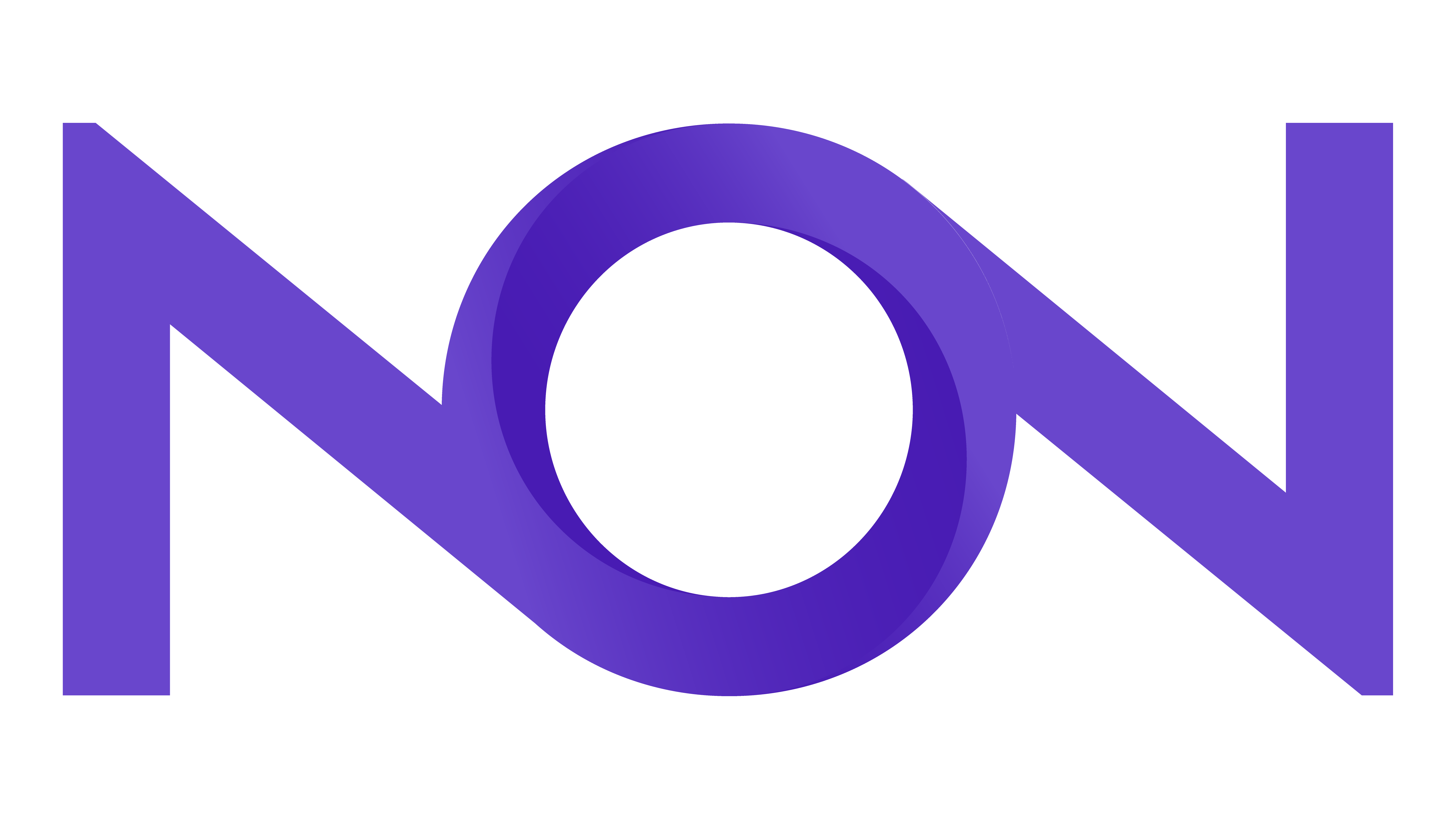









💬 Comments (0)
Bergabung dengan 0 orang yang sudah berkomentar. Apa pendapatmu?
Belum ada komentar untuk berita ini.